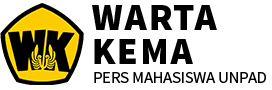Bro orangnya tak terkenal. Tulisannya tak satu pun pernah nangkring di halaman buku pelajaran Bahasa Indonesia. Kehadirannya absen selalu dari kanon sastra. Hanya satu persoalan Bro yang dikenal orang ramai: nama belakangnya.
Bro, alias Sobron Aidit, lahir di Belitung pada tahun 1934. Nama ibunya Marisah, sedang ayahnya bernama Abdullah Aidit. Nama ‘Aidit’ jelas Bro dapatkan dari sang ayah. Sayangnya, tiap kali mendengar nama ‘Aidit’, rakyat Indonesia kebanyakan memilih bergidik, meringis, atau malah mundur ketakutan.
Sobron memang merupakan adik tiri Dipa Nusantara Aidit, seorang mantan ketua Partai Komunis Indonesia (PKI) yang terakhir, tepat sebelum partai ini habis dilanda badai TAP MPRS XXV. Nasib Bro tak bisa dibilang beruntung, tapi setidaknya ia punya takdir sedikit lebih baik dari sang kakak. Nyawa Bro tak dihabisi saudara sebangsanya. Cangkul Pulau Buru pun tak pernah ia cicipi. Bro banyak hidup berpindah, mulanya ia bekerja jadi wartawan Peking Review di Tiongkok. Beberapa tahun pasca Revolusi Kebudayaan yang diinisiasi Mao, Bro pindah ke Paris dan kemudian membuka restoran khas Indonesia di sana.
Bro cukup terkenal sebagai seorang penyair pada masa kepresidenan Soekarno. Tulisannya raib tak berbekas ketika Orde Baru menduduki tampuk kekuasaan. Puisi dan cerpennya dihilangkan, Bro kemudian resmi jadi sosok terlarang. Sayangnya, hingga kini nama Bro masih jarang disebut pada diskusi-diskusi sastra.
Ada satu puisi Bro yang bikin saya terhenyak. Begini bunyinya.
Bagi yang Tidak Mengerti
Sedungu dan sekelu itu dia menjalani benuanya
membuat kami berani berkata
tenang-tenang kukatakan dalam dirinya:
tahu tuan, dari mana kami ini?
Dan dia mematungkan diri di keleluasaan padang
dari jauh tampak—mata kami yang melihatnya dengan sayu
berlari bangsa jenisnya merebut arca itu, arca emas
lagi kami bertanya: tuan, sudahkah tuan merantau di benua kami?
Berebutan bangsa jenisnya berpeluk
arca hitam, arca emas—sampai batas
di mana dia melahirkan putri, melahirkan putra
sedang kami menantu untuk membawanya ke kedua kutub
dan dia tidak mengerti
lagi kami membuka suara: tuan, benua apa di sebelah benua ini
yang paginya dan malamnya selalu bercahaya
dan tidak juga tuan kenal
tidak tuan mau berjumpa lama
Puisi ini sejatinya pernah dimuat pada Majalah Indonesia pada Juni 1951 lalu. Sejauh pemahaman saya, yang tentu tak bersanding dengan kata precise—tapi karena indah puisi terletak pada ragam tafsir yang dihasilkannya—Bro bicara soal kolonialisme. Arca emas arca hitam, bisa jadi merujuk pada segala sesuatu yang jadi tujuan pihak kolonial. Bisa rempah, bisa budak, bisa gundik, bisa juga hegemoni pengetahuan.
Kolonialisme adalah isu yang kehadirannya terasa begitu jauh. Untuk mengingatnya kembali, kita seolah harus melompat melintasi ruang dan waktu. Ada puluh hingga ratus tahun yang perlu dilangkahi, ada setting tempat yang perlu diganti. Tapi alih-alih memikirkan pribumi kelaparan di belantara Jawa, yang kita pikirkan justru suasana kantuk ketika mendengar celoteh guru Sejarah semasa SMA. Isu soal kolonialisme jadi sulit dijangkau orang banyak; ia punya kaitan erat dengan peristiwa lampau yang sudah selesai.
Perjumpaan dengan praktik kolonialisme terjadi hampir setiap hari. Hegemoni pengetahuan satu contohnya. Praktik ini terjadi tiada henti, sifatnya lembut menyusup tanpa pernah kita sadari. Dunia rasanya sudah hampir kiamat, tapi saya masih harus memahami teori antropolog yang dapat kucuran milyar dana dari CIA. Belum lagi ratusan catatan etnografi milik Belanda yang super bias. Sedang ini baru jurusan saya, belum lagi program studi para pembaca sekalian.
Diskusi soal kolonialisme di Indonesia kiranya terus berkembang. Meski begitu, beberapa di antaranya tak jarang yang bergerak mundur. Beberapa percakapan di Tiktok dan Twitter sempat bicara soal betapa murah hatinya penjajah Belanda yang ‘membantu’ pribumi keluar dari ketertinggalan zaman. Selain itu, tak sedikit rakyat Indonesia yang mencibir Mbak Rara, pawang hujan di Mandalika kemarin. Katanya, aksi Mbak Rara ditertawai para pembalap bule, dan oleh karenanya kita harus ikut merasa malu sebagai bangsa Indonesia. Praktik-praktik semacam ini, saya kira, kaitannya erat sekali dengan perasaan inferior yang tanpa sadar sudah tertanam lebih dahulu dalam diri kita. Orang kulit putih selalu unggul dan superior dalam berbagai hal, sedang kita bangsa kulit berwarna selalu ada jauh di bawahnya.
Tapi ada benarnya ucapan Bro. Bro, yang dalam cerpen Martin Aleida dikatakan ‘sedang berenang-renang ke surga’, tak keliru soal ‘berebutan bangsa jenisnya berpeluk arca hitam, arca emas’. Meski begitu, secinta dan sekagum apa pun saya pada Bro, tetap tak ingin saya biarkan larik ‘sedang kami menantu untuk membawanya ke kedua kutub’ terus hidup sebagai kenyataan. Dan saya harap saya tak sendiri.
Penulis: Alissa Wiranova
Editor: Fahmy Fauzy M.