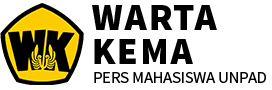Di tengah hiruk-pikuk perayaan Hari Buruh (May Day), sebuah seminar penting dengan judul “Relasi Sipil-Militer: Perebutan Ruang Budaya dan Masa Depan Demokrasi” diselenggarakan oleh Departemen & Program Studi Antropologi Universitas Padjadjaran dan Laboratorium Antropologi Politik, Kebijakan, dan Pembangunan Universitas Padjadjaran. Ironisnya, ruang seminar tampak lengang, bukan karena publik tidak peduli terhadap demokrasi, tetapi karena momentum seminar ini bertabrakan dengan medan ekspresi rakyat yang paling otentik, yaitu aksi turun ke jalan.
Seminar tersebut mengulas secara kritis bagaimana relasi sipil dan militer membentuk dinamika kekuasaan serta menyusup ke ruang-ruang budaya. Sayangnya, seminar ini hadir di ruang dan waktu yang salah. Hal ini bukan karena substansi materinya yang lemah, melainkan ketidaksanggupan membaca irama sosial di luar dinding kampus.
Seminar ini seharusnya menjadi ruang penting untuk menautkan analisis struktural dengan realitas sosial. Namun, pelaksanaannya justru bertabrakan dengan mobilisasi massa buruh, sehingga ruang diskusi ini kehilangan fungsinya sebagai jembatan antara refleksi akademik dan gerakan aksi. Demokrasi bukan hanya soal pemilu atau kebebasan formal, melainkan kemampuan masyarakat untuk mengenali, membedah, dan merespon kuasa dalam segala bentuknya.
Kursi-kursi kosong dalam seminar itu bukan hanya soal partisipasi yang rendah, melainkan soal ketidakhadiran strategi yang seharusnya menyatukan pikiran dan tindakan. Dalam demokrasi yang cukup kompleks, kampus tidak cukup hanya bicara dari balik meja. Kampus juga harus sanggup membaca waktu dan tahu kapan saatnya mendengarkan suara jalanan, karena jika tidak, ruang akademik akan terus bicara sendiri, apalagi ketika banyak massa aksi berjuang di jalanan.
Seperti yang telah dijelaskan oleh Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia (UI), Sulistyowati Irianto, “Jalan keluar dari krisis ini adalah jalan kebudayaan. Kita harus merestorasi demokrasi dari akar: dari rakyat, dari budaya, dari sejarah kita sendiri.”
Itu artinya kampus tidak boleh terus terjebak dalam dinding-dindingnya sendiri. Kampus harus bisa hadir bersama rakyat, mendengar denyut jalanan, dan tahu kapan harus ikut berbaris. Jika kampus ingin tetap relevan dalam demokrasi yang sedang diuji, maka kampus harus sanggup menjembatani teori dan tindakan. Jika tidak, kampus akan terus bicara sendiri tanpa makna, sementara rakyat berteriak di jalanan.
Dalam salah satu sesi, Sulistyowati, menyampaikan kekhawatiran mendalam terhadap kondisi negara hukum dan demokrasi saat ini.
“Yang terjadi hari ini adalah otoritarianisme yang menggunakan hukum sebagai alat untuk mendefinisikan kekuasaan,” tegasnya.
Ia menyebutkan situasi saat ini menciptakan kekerasan budaya yang dapat menumpulkan kesadaran kritis masyarakat dalam bentuk dominasi yang masuk lewat simbol, narasi, dan platform digital.
Namun, gagasan kritis ini hanya bergema di antara kursi-kursi kosong karena publik yang semestinya terlibat dalam diskusi ini justru sedang aktif membangun kesadaran melalui aksi massa di luar sana.
Sementara itu, Mayjen TNI sekaligus dosen Universitas Pertahanan Indonesia, Nugraha Gumilar, mencoba untuk meredam kekhawatiran publik dengan mengatakan bahwa TNI tetap berkomitmen pada tugas pokok konstitusionalnya sebagai pendukung sipil, bukan sebagai pemegang kuasa.
“Kami hadir sebagai pendukung sipil, bukan pengambil alih. Peran kami dalam bencana, vaksinasi, atau pendidikan di wilayah konflik adalah bentuk dukungan terhadap rakyat,” jelasnya.
Namun, dalam konteks sipil yang lemah, “dukungan” dapat menjadi ruang abu-abu yang rentan menjadi dominasi jika tidak ada pengawasan dan keseimbangan. Disinilah pentingnya ruang akademik untuk tak hanya mengamini, tetapi juga menguji setiap klaim kekuasaan dengan kecurigaan metodologis. Sayangnya, saat ruang diskusi ini lengang, fungsi kritis itu pun melemah.
Penulis: Salwa Nabila Ayu
Editor: Alifia Pilar Alya Hasani, Fernaldhy Rossi Armanda